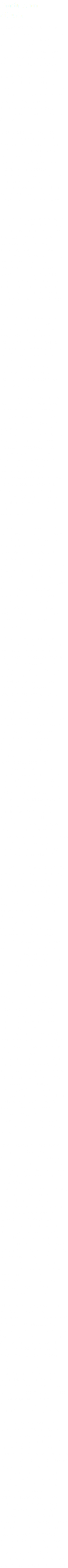Scroll Down
Kita dasarkan perjuangan sekarang ini atas dasar kesucian. Kami yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan melalaikan hambanya yang memperjuangkan sesuatu yang adil berdasarkan kesucian batin …. Kita insya Allah akan menang jika berjuang kita sungguh berdasarkan kesucian, membela kebenaran dan keadilan (1948).
SHARE
Apa yang Anda lakukan saat berusia 30 tahun? Bagaimana bila Anda diserahi tanggung jawab menjadi panglima Tentara Rakyat Indonesia di usia itu? Tugasnya macam-macam: Mengatur tentara dan laskar yang jumlahnya ratusan ribu dan belum terorganisasi. Menyiapkan struktur organisasi tentara modern. Memadamkan pemberontakan kawan seperjuangan. Menghadapi macam-macam politisi dari berbagai partai. Menyiapkan armada perang menghadapi Belanda dan Inggris. Bergerilya di hutan, gunung, sungai, desa dengan ditandu. Beranikah Anda menerima tanggung jawab sebesar itu? Perkenalkan, Soedirman (29 tahun), putra petani kelahiran Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, yang mengambil lowongan prestisius tersebut.
Soedirman jelas memiliki beban berat. Ia harus mengonsolidasikan kekuatan tentara yang terserak dan milisi-milisi lokal di seluruh nusantara. Setiap milisi memiliki panglima dan ketuanya tersendiri dan aliran politik ataupun organisasi masyarakatnya masing-masing. Saat itu pula ada dua faksi besar di militer Indonesia, yakni: Faksi Pembela Tanah Air (PETA) dan faksi Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL). PETA adalah program bantuan militer bentukan penjajah Jepang. Sementara, KNIL ada program bentukan penjajah Belanda. Selain itu, Soedirman juga harus berhadapan dengan bermacam watak dan arah politik para tokoh kemerdekaan. Yang satu ingin menarik ke kiri, yang lain ingin ke belok kanan. Ada yang bersikukuh tetap di tengah. Ada tokoh yang ingin revolusioner. Ada yang kokoh harus menjalankan diplomasi perlahan. Pada saat yang sama, ancaman serangan selalu datang dari tentara Belanda yang tidak ingin membiarkan Indonesia merdeka. Dari sini kita bisa melihat, kapasitas kepemimpinan dan manajerial apa yang dimiliki Soedirman untuk bisa menengahi itu semua. Lantas, bagaimana karakter dan kapasitas ini terbentuk? Seperti apa Soedirman kecil sampai remaja membangun dirinya?
Wong Cilik dan Priayi
Kementerian Pertahanan pada 1977 menegaskan Soedirman lahir pada 24 Januari 1916. Bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 1336 Hijriyah. Versi lokal menyebutkan, Soedirman lahir pada Senin Pon di bulan Maulid. Orang tuanya, ditegaskan juga oleh Kemenhan, adalah Karsid Kartawiradji dan Sijem. Keluarga Soedirman bermukim di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Namun, sejak bayi, Soedirman sudah ikut pamannya, R Tjokrosunaryo, bermukim di Rembang. Sang paman yang hidupnya jauh lebih berkecukupan ketimbang orang tua kandung Soedirman. Tjokrosunaryo menjadi asisten wedana (camat) Rembang. Setelah pensiun, ia pindah ke Cilacap. Pamannya disebut menjadi pedagang mesin jahit dan penasihat pengadilan negeri Cilacap. Di sini, Soedirman menghabiskan masa remaja dan dewasanya.
Soedirman dibesarkan dalam perpaduan dua subkultur di Jawa. Sardiman, dalam bukunya, Panglima Besar Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah (2000) menegaskan lingkungan keluarga besar Soedirman kental kultur wong cilik dan kultur priayi. Kultur wong cilik ia dapat dari keluarga aslinya, sementara kultur priayi dididik oleh keluarga pamannya. Laku kultur yang pertama itu, di antaranya kesederhanaan, prihatin, kerja keras, kerja fisik, seperti membersihkan rumah, menyirami tanaman, mengambil air untuk mengisi bak mandi, mengambil air untuk memasak, mengisi padasan untuk wudhu, mencuci piring, cangkir, dan alat rumah tangga lainnya. Termasuk juga Soedirman ngemong adiknya satu-satunya, Mohammad Samingan.
Sementara dari kultur priayi, menurut Sardiman, Soedirman diajarkan adat adiluhung, adat istiadat, sopan santun, unggah-ungguh, menghargai akhlak, bermulut baik, patuh dan hormat orang tua. Salah satu contoh yang pernah terekam soal Soedirman cilik adalah saat ayah angkatnya, R Tjokrosunaryo, bertamu ke kediaman R Sumoyo. Sumoyo adalah tokoh Boedi Oetomo lokal. Pamannya dan Sumoyo bercakap-cakap di ruang dalam. Sementara, Soedirman tetap menunggu di luar sambil duduk bersila. Ia baru masuk saat namanya dipanggil. Dengan laku dodok atau berjalan jongkok, Soedirman menghampiri pamannya.
Majalah Senakatha Pusjarah TNI edisi 100 Tahun Soedirman (2016) juga memotret masa kecil Soedirman dari sisi pendidikan keagamaan Soedirman. Layaknya anak desa umumnya, ia mengaji di surau dengan ulama lokal. Soedirman kerap mengajak adiknya, Moh Samingan, ke surau.
Menurut kesaksian Siti Sukiyah, anak Moh Samingan, ayah, dan pamannya belajar mengaji pada KH Qahar. Keduanya belajar mengaji mulai dari turutan atau Juz 'Amma baru kemudian pindah ke Alquran utuh sampai khatam. Soedirman lancar membaca Alquran. Soedirman kecil juga dikenang memiliki suara yang cukup bagus. Meski karakternya pendiam, ia kerap ditunjuk untuk menjadi penyiar azan dan iqamat di surau oleh teman-temannya.
Selain mempelajari baca tulis Alquran, Soedirman juga belajar tentang Islam secara lebih luas. Pemahaman agama Soedirman kecil disebut-sebut jauh melebihi rekan-rekannya. Ia menjadi pembantu guru agama. Soedirman mendapat pendalaman Islam dari guru sekolahnya, yakni Pak Saidun dan tokoh Muhammadiyah setempat R Moh Kholil Marto Saputro. Oleh kawan-kawannya ia sempat disebut sebagai 'hajine' alias 'pak haji kecil' karena sikap dan perilakunya yang agamis.
Moh Samingan, dalam wawancaranya dengan TNI AD pada 1970, mengingat: Kakaknya jarang sekali tidur sebelum tengah malam. Selain itu, Soedirman dikenang rajin puasa sunah dan tak lepas salat Tahajud. Dalam satu kejadian saat pamannya meninggal dan keluarga tak punya uang untuk Soedirman melanjutkan sekolah menengahnya, laku prihatin dijalankan. "Soedirman biasa tidur di lantai beralaskan tikar yang ditempatkan di dekat jendela di sisi kanan rumahnya," kata Samingan. Sang adik akhirnya mengikuti kebiasaan ini. Keduanya tidur di atas tikar di lantai dengan kepala menghadap ke jendela. Dengan begitu, kedua kepala kakak beradik ini membentuk sudut 90 derajat.
Nostalgia tidur di tikar ini pernah diulangi Soedirman saat ia sudah menjadi Panglima Besar. Kisahnya pada akhir 1946 Soedirman melawat ke Purwokerto untuk memberi pejelasan soal dampak Perjanjian Linggarjati pada pejabat sipil dan militer di sana. Selepas salat Jumat, Soedirman mampir sejenak menengok adiknya di Kota Cilacap. Panitia persiapan sudah menyewa satu kamar losmen untuk Soedirman. Ia meminta Moh Samingan untuk mampir ke losmennya. Di sini kedua kakak beradik itu mengobrol sampai larut malam. Ia meminta Samingan menginap, "Tidur di sini saja, Dik." Panglima lalu meminta tikar ke pengawalnya di luar. Tikar ia gelar di dekat jendela kamar. Di atas tikar ini lalu kakak beradik itu tidur seperti saat mereka kecil dulu. "Seperti dulu ya, Dik. Kau membujur ke sana, aku membujur ke sini." Kasur empuk di atas dipan losmen dibiarkan menganggur. []
Tempat Tanggal Lahir
24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Wafat
29 Januari 1950
Silsilah
Ayah: Karsid Kartawiradji
Ibu: Sijem
Paman: R Tjokrosunaryo
Bibi: Tarsem
Keluarga
Istri: Afiah
Anak:
1. Ahmad Tidarwono
2. Taufik Effendi
3. Didi Praptiastuti
4. Didi Sutjiati
5. Didi Pudjiati
6. Titi Wahjuti Setyaningrum
7. Muhammad Teguh Bambang Tjahjadi
Pendidikan
- Holandsche Indlandsche School (HIS) Cilacap
- Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO) Perguruan Parama Wiworo Tomo
- Hizbul Wathan Muhammadiyah
Pekerjaan
- Guru HIS Muhammadiyah
- Kepala Sekolah HIS Muhammadiyah
- Pendiri Koperasi Dagang Perkoperasian Bangsa Indonesia, Cilacap
- Pendiri Persatuan Koperasi Indonesia Wijayakusuma Cilacap
- Pembina Badan Pengurus Makanan Rakyat
- Anggota Syu Sangikai Karesidenan Banyumas
- Anggota Hokokai Karesidenan Banyumas
Karier Militer
- PETA Angkatan II Bogor
- Daidanco Kroya, Banyumas, Jawa Tengah
- Ketua Badan Keamanan Rakyat Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah
- Pangkat Letkol, Komandan Resimen I Divisi I Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
- Pangkat Kolonel, Komandan Divisi V TKR Banyumas, Jawa Tengah
- Pangkat Jenderal Panglima Tertinggi TKR (12 November 1945)
- Pangkat Jenderal Panglima Besar TKR (18 Desember 1945)
- Pangkat Jenderal Panglima Besar TRI (25 Mei 1946)
- Pangkat Jenderal Panglima Besar TNI
SOEDIRMAN
Stevy Maradona
Redaktur
Kreatif
D. Purwo Widjianto
Baskoro Adhy
Nur Adi Wicaksono
Gilang EF
![Pandu Islam di Dada Di dalam setiap penulisan riwayat hidup Soedirman, selalu terselip soal babak ia masuk kepanduan Muhammadiyah, Hisbul Wathan, pada awal 1930-an. Sedianya babak hidup Soedirman yang ini menjadi amat menarik. Karena gerakan kepanduan di Indonesia di awal abad ke-20 ternyata memiliki muatan politis nasionalisme yang kental. Karena itu, tidak berlebihan kiranya kalau kita menyebut babak kepanduan Hisbul Wathan ini adalah salah satu faktor yang membentuk karakter nasionalisme Soedirman. Kepanduan di Indonesia dibawa oleh dua tokoh penjajah Belanda, PJ Smith dan Mayor de Jager, pada 1913-1914. Tujuan mereka saat itu untuk melatih anak-remaja Belanda usia 12-18 tahun menjadi warga negara yang baik, disiplin, berkarakter bela Ratu Belanda, bela tanah air Belanda, gemar menolong, cinta lingkungan. Organisasi pandu awal diberi nama Nederlandsche-Indische Padvindersvereeniging (NIPV). Dalam tulisannya yang merangkum gerakan kepanduan di Indonesia, "Padvinders, Pandu, Pramuka: Youth and State in the 20th Century Indonesia (2011)" pengajar antropologi UGM Pujo Semedi mengatakan, ada perbedaan yang mencolok soal latar sosial kepanduan di Indonesia saat itu dengan di Eropa. Kepanduan di Eropa menyeruak di tengah situasi antarnegara saling perang dan generasi muda yang gamang bin galau menghadapi hidup di tengah perang. Sementara di Indonesia, terutama di tingkat lokal nanti akan terlihat, kepanduan justru amat kental dibayangi atmosfer kebangkitan nasional dan perlawanan melawan penjajah Belanda. Dari kepanduan gaya Belanda ini, tokoh-tokoh nasional saat itu melihat ada kesempatan yang baik untuk menanamkan nilai nilai awal nasionalisme ke generasi muda prakemerdekaan. Lahirlah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) pada 1916. Yang memelopori adalah Pangeran Mangkunegara VII di Surakarta. Sesuai dengan namanya, setiap anggota pandu JPO harus setia kepada keraton, kepada Sri Sultan, dan kepada Tanah Jawa. Anggota JPO saat itu terbatas di lingkaran keraton. Saban Ahad mereka dijadwalkan berlatih di halaman depan keraton. Latihannya mencakup baris-berbaris, pertolongan kecelakaan, tali-temali, membaca peta, dan kepanduan dasar lainnya. Para pandu anak-remaja yang diberi seragam itu berlatih terbuka, dapat dilihat oleh warga yang lalu lalang di depan pagar keraton. Pandu nasionalisme dan agamis Dalam riwayat resmi Hisbul Wathan yang dirilis oleh Muhammadiyah dan organisasi itu sendiri dikisahkan, latihan kepanduan JPO ini menarik minat pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Suatu waktu pada 1916, usai kembali dari pengajian Sidiq Amanah Fathonah Tabligh di Surakarta yang rutin diadakan di kediaman KH Imam Mukhtar Bukhari, lewatlah rombongan KH Ahmad Dahlan di depan halaman Mangkunegaran. Ia melihat bagaimana pandu-pandu muda JPO berlatih berbaris. Ini memberinya ide. KH Ahmad Dahlan ingin agar peserta didik Muhammadiyah pun memiliki kegiatan serupa untuk mengembangkan perjuangan, syiar Islam, berbakti kepada Allah SWT, mendidik disiplin, dan menyehatkan raga. Sampai di Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan secara khusus membahas untuk membentuk kepanduan Muhammadiyah. Ia memanggil dua pengajar yakni Sumodirjo dan Sarbini untuk merintis gerakan kepanduan Muhammadiyah. Sarbini kebetulan bekas opsir Belanda yang pernah merasakan pendidikan tentara. Dengan sederhana, mulailah keduanya melatih pemuda Muhammadiyah kepanduan di halaman sekolah di Suronatan. Baris-berbaris, pertolongan kecelakaan, olahraga. Latihan ini masuk ke dalam aktivitas di luar sekolah Muhammadiyah. Tidak butuh lama, pemuda kauman yang melihat siswa Muhammadiyah berlatih kepanduan banyak yang tertarik. Guru-guru pun ikut berlatih. Pada 1918, akhirnya Muhammadiyah memiliki Padvinders Muhammadiyah, yang kemudian diganti dengan nama Hisbul Wathan (cinta tanah air) pada 1921, terinspirasi oleh gerakan perjuangan Partai Wathan yang beraliran antikolonialisme di Mesir. Muhammadiyah dan Boedi Oetomo adalah dua organisasi massa yang ketika itu mengikuti Pangeran Mangkunegara VII membentuk kepanduan. Dengan demikian, pada saat itu sudah muncul kepanduan lokal, yakni JPO, Hisbul Wathan, Nationale Padvinderij (milik Boedi Oetomo), dan kemudian Java Padviderij (milik Jong Java). Secara senyap, inilah cara-cara awal pergerakan prakemerdekaan mendidik generasi muda ketika itu untuk mencintai Tanah Air dan melawan penjajahan. Karena situasi politiknya belum memungkinkan untuk membuat perlawanan langsung. Semboyan Hisbul Wathan pada waktu itu adalah setia kepada ulil amri, sungguh berhajat akan menjadi orang utama, tahu akan sopan santun dan tidak akan membesarkan diri, boleh dipercaya, bermuka manis, hemat dan cermat, penyayang, suka pada sekalian kerukunan, tangkas, pemberani, tahan, serta terpercaya, kuat pikiran, menerja segala kebenaran, ringan menolong dan rajin. "Membantu orang-orang tua dan guru guru dalam mendidik dan anak-anak dan supaya kelakuannya menjadi orang Islam yang berarti (sempurna) ialah orang yang berbudi pekerti baik, berbadan sehat, berguna bagi diri sendiri dan bagi umum, takwa kepada Allah, artinya menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya." seperti dikutip dari Pasal 2 Boekoe Peratoeran Hizboel Wathan. Sementara muatan nasionalisme terangkum di dalam kode kehormatan Hizbul Wathan seperti Pasal 1 Janji Pandu Hizbul Wathan yang berbunyi: "Setia menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan UU tanah airku." Secara umum, ada tiga kegiatan yang harus diikuti Soedirman sebagai pandu Hizbul Wathan. Pertama adalah program pendidikan rohani sebagai wahana pembentukan karakter. Kedua, pendidikan jasmani untuk pengembangan kesehatan dan fisik. Ketiga program karya bakti sebagai wujud pengamalan pandu. Untuk yang terakhir ini, Soedirman diharuskan aktif di Majelis Penolong Kesengsaraan Oemat (PKO) Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang mengumpulkan zakat, menyelenggarakan shalat Id, menyembelih hewan kurban dan membagikannya ke warga, ketertiban warga, dan lainnya. Inilah atmosfer yang dimasuki oleh remaja Soedirman pada pertengahan 1930-an. Dalam biografi resmi yang dirilis Pusat Sejarah TNI disebutkan: "Melalui kegiatan Hizbul Wathan bakat bakat kepemimpinan Soedirman terlihat. Ia menjadi pandu yang disiplin, militer, dan bertanggung jawab, cinta terhadap alam." Dalam satu kisah perkemahan pandu Hizbul Wathan di lereng Batur di daerah Dieng Wonosobo, di versi lain disebutkan perkemahan dilakukan di lereng Gunung Slamet, terlihat bagaimana remaja Soedirman bersikap menghadapi situasi dan kondisi yang ekstrim. Menjelang malam, turun hujan deras. Udara menjadi sangat dingin. Para pandu rekan Soedirman yang tak kuat dingin meminta izin untuk pindah tenda atau turun ke rumah penduduk. Soedirman tetap di dalam tendanya. Satu rekan Hizbul Wathan yang bertugas jaga malam mengatakan sempat mendengar lantunan ayat Kursi dari dalam tenda Soedirman. Setelah itu, ia terlihat mengenakan baju hangat dan menunaikan shalat malam. Dalam buku Soedirman Seorang Panglima Seorang Martir (2012) ditegaskan bahwa watak disiplin dan tanggung jawab yang Soedirman miliki hingga menjadi Panglima Besar awalnya memang dipupuk di kepanduan Hisbul Wathan. Di sini, Soedirman berprestasi dari seorang pandu pemula menjadi ketua pandu Hisbul Wathan Cilacap dan Menteri Daerah Hisbul Wathan Banyumas. []](images/blank.gif?crc=4208392903)
repro buku panglima besar jenderal soedirman, tjokropranolo